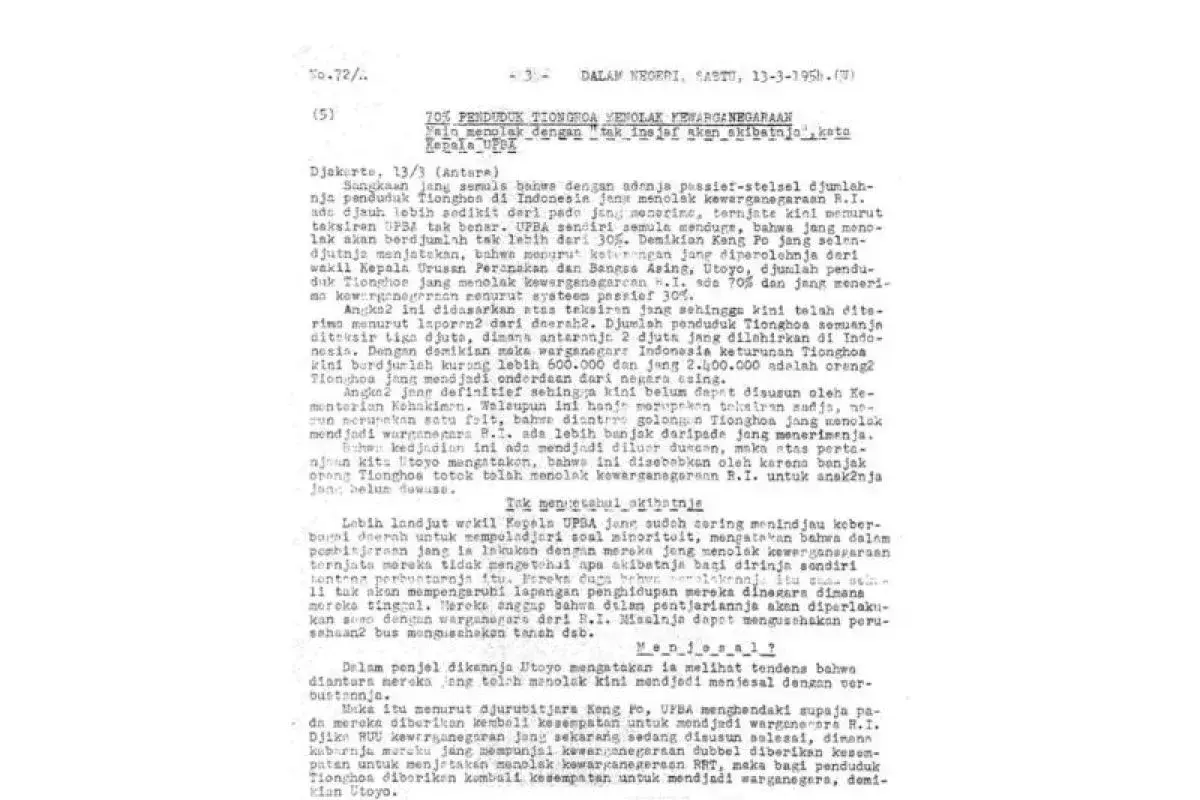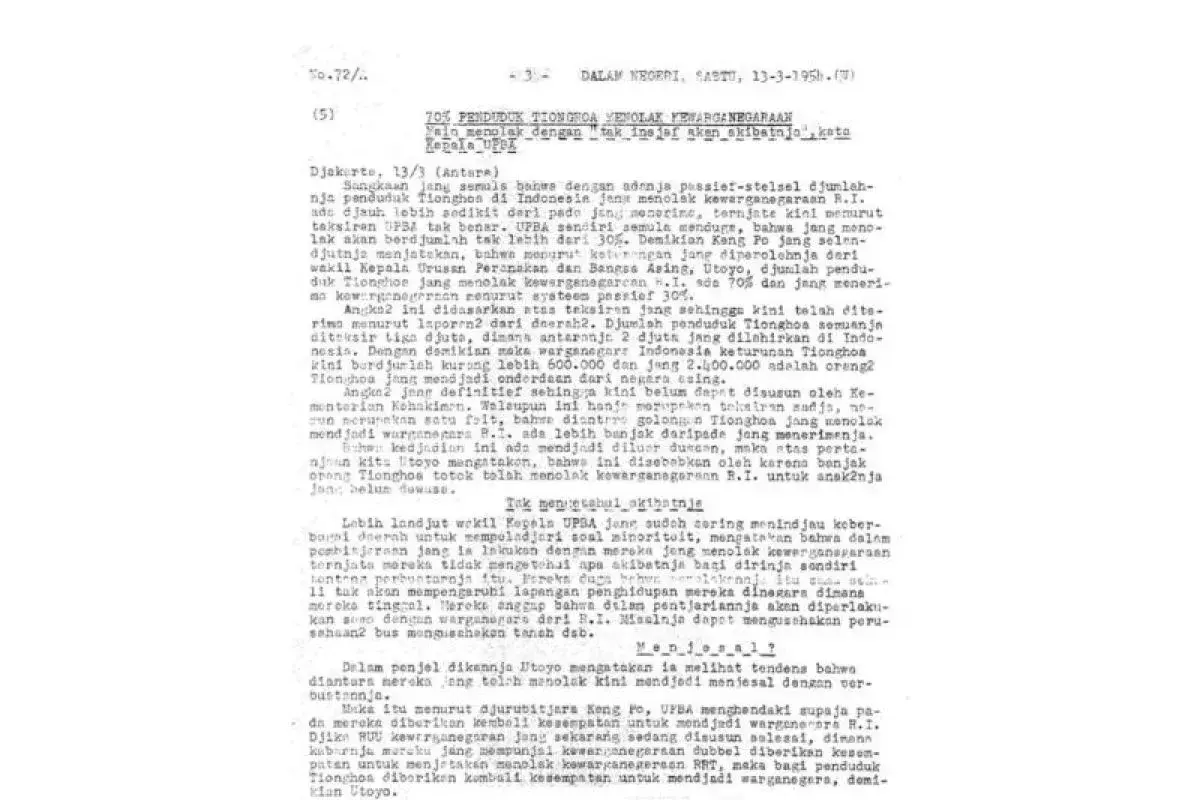Pantau - Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat ke permukaan dan ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun media arus utama.
Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa sistem pemilihan oleh DPRD dinilai selaras dengan sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Namun, banyak kalangan menilai bahwa pilkada langsung justru merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.
Korupsi dan Biaya Politik Tinggi Jadi Dalih Revisi Sistem
Salah satu alasan utama yang mendorong munculnya wacana pemilihan oleh DPRD adalah anggapan bahwa pilkada langsung berbiaya mahal dan menjadi akar dari praktik korupsi di daerah.
Oknum yang mencalonkan diri dalam pilkada disebut terpaksa melakukan berbagai tindak korupsi demi mengembalikan modal, seperti pemerasan, jual beli jabatan, hingga penggelembungan anggaran.
Tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK pada 2025 adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Mereka tersandung kasus suap, pemerasan, dan jual beli jabatan, yang tergolong dalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam UU tersebut, bentuk-bentuk korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan, pemalsuan dokumen, pemerasan oleh pejabat publik, hingga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Data KPK pada Mei 2025 mencatat bahwa sejak 2024 hingga pertengahan 2025, terdapat 201 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari 171 bupati/wali kota dan 30 gubernur.
Solusi: Perbaiki Sistem, Bukan Mundur dari Pemilu Langsung
Banyak pihak menilai bahwa perbaikan sistem lebih diperlukan ketimbang menghapus pilkada langsung.
Salah satu solusinya adalah menekan biaya politik dengan mendorong calon kepala daerah membangun modal sosial yang kuat — melalui relasi, jaringan kepercayaan, dan pemahaman terhadap masyarakat.
Negara juga didesak untuk menindak tegas partai politik yang mematok mahar politik, bahkan bila perlu mendiskualifikasi mereka dari pemilu.
KPU juga disarankan untuk mendiskualifikasi kandidat yang terbukti melakukan praktik politik uang atau memberikan mahar.
Pemerintah dinilai perlu hadir dengan memberikan bantuan dana kampanye bagi calon resmi, agar tidak seluruh beban biaya politik dibebankan pada individu kandidat.
Pertanyaan soal kemampuan negara membiayai kampanye ribuan pasangan calon memang relevan, mengingat pemilu akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Namun, hal ini kembali pada komitmen pemerintah terhadap demokrasi.
Amendemen dan Tafsir UUD 1945 Jadi Perdebatan
Isu kembalinya sistem pilkada oleh DPRD memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan kembalinya sistem lama seperti dalam naskah asli UUD 1945.
Sejak reformasi, UUD 1945 telah diamendemen empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Amendemen tersebut melahirkan berbagai lembaga dan prinsip baru seperti pembatasan masa jabatan presiden, otonomi daerah, pemisahan TNI-Polri, perlindungan HAM, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Jika kembali ke UUD versi awal, ada kekhawatiran lembaga seperti MK bisa dibubarkan dan DPA dihidupkan kembali.
Meskipun Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebut pemilihan langsung, istilah “dipilih secara demokratis” diinterpretasikan sebagai pemilu yang bebas dan adil, sesuai prinsip kedaulatan rakyat.
Karena itu, tafsir hukum atas konstitusi seharusnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal utama UUD NRI 1945.
- Penulis :
- Gerry Eka